
Sastra, Swa News- Rabu malam (20/11/24), saya menyempatkan diri menghadiri acara Srehbungareh-Midway di IQ Coffee tentang fomo. Sebuah ruang diskusi yang hangat, di mana berbagai kalangan—mahasiswa, pedagang, driver ojol, guru, pekerja sosial, hingga pegiat literasi—berkumpul untuk berdiskusi dan mengobrol santai.
Tema yang diangkat kali ini cukup menarik: “Does Every One FOMO?”
FOMO, singkatan dari Fear of Missing Out, adalah fenomena yang cukup akrab di telinga generasi muda. Rasa cemas dan khawatir akan ketinggalan tren, baik itu dalam hal gaya hidup, teknologi, atau media sosial, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Fenomena FOMO, menurut salah satu peserta diskusi, erat kaitannya dengan fenomena dromologi, sebuah kondisi di mana kita hidup dalam ritme yang semakin cepat dan serba instan.
FOMO seakan menjadi “epidemik” di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Pertumbuhan pesat media sosial dan internet telah menciptakan lingkungan di mana setiap orang seolah-olah hidup dalam sorotan. Pembaruan status, foto-foto liburan, dan pencapaian pribadi terus bermunculan di beranda, menciptakan perasaan seolah-olah kita selalu ketinggalan sesuatu.
Baca juga:
Generasi milenial dan Gen Z tumbuh di era di mana konektivitas menjadi hal yang sangat penting. Mereka terbiasa mendapatkan informasi secara instan dan terus-menerus terhubung dengan orang lain. Hal ini membuat mereka rentan mengalami FOMO, karena mereka terus-menerus membandingkan hidup mereka dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial.

Di samping itu, generasi milenial dan Gen Z sering juga disebut sebagai “digital native”. Mereka lahir dan tumbuh di era digital, di mana teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kedekatan mereka dengan teknologi ini membuat mereka sangat rentan terhadap FOMO.
Sebagai digital native, generasi muda memiliki akses yang mudah dan hampir tanpa batas terhadap informasi. Mereka terbiasa dengan kecepatan dan instant gratification yang ditawarkan oleh dunia digital. Namun, di sisi lain, hal ini juga membuat mereka merasa tertekan untuk selalu “up-to-date” dan tidak ingin ketinggalan tren terbaru.
Sementara itu, FOMO dan asketisme tasawuf merupakan dua konsep yang sangat bertolak belakang. Jika FOMO mendorong kita untuk terus-menerus mengejar kepuasan duniawi, asketisme mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari belenggu duniawi dan fokus pada pengembangan spiritual. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip asketisme, kita dapat mengatasi FOMO dan menemukan kebahagiaan sejati.
Di tengah obrolan tentang FOMO dan Tasawuf, saya tak bisa lepas dari pandangan pada dinding-dinding IQ Coffee. Lukisan-lukisan estetik bertema tasawuf, perlawanan kelas, dan budaya urban seakan menjadi kontras sekaligus menarik dengan tema diskusi tersebut. Tasawuf, yang mengajarkan tentang penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Tuhan, seolah menjadi semacam obat penawar bagi hiruk pikuk dunia yang penuh dengan FOMO.
Diskusi malam itu mengingatkan saya bahwa di tengah arus informasi yang begitu deras, kita perlu berhenti sejenak untuk merenung. Apakah segala sesuatu yang sedang kita kejar itu memang penting? Apakah kita sudah hidup seutuhnya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, namun jawabannya tidak selalu mudah.
Srehbungareh-Midway bukan hanya sekadar ajang diskusi, tetapi juga sebuah ruang untuk saling berbagi dan belajar. Di sini, kita diingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada hal-hal materi atau pengakuan sosial. Kadang, kebahagiaan yang sesungguhnya bisa kita temukan dalam hal-hal sederhana, seperti pertemanan, keluarga, dan kegiatan yang kita sukai.



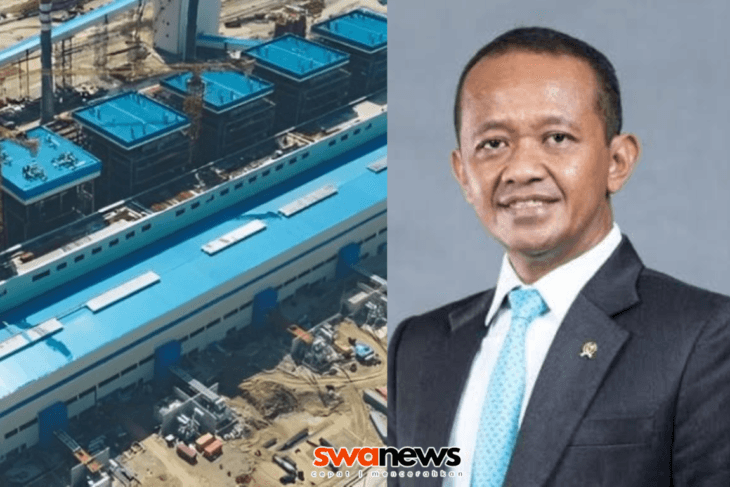















One thought on “Srehbungareh-Midway: Ketika Budaya FOMO Berdiri di Persimpangan Tasawuf”