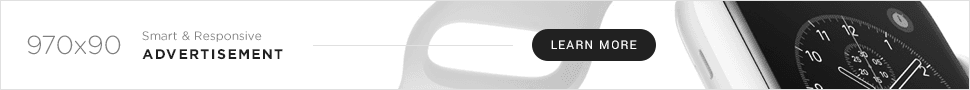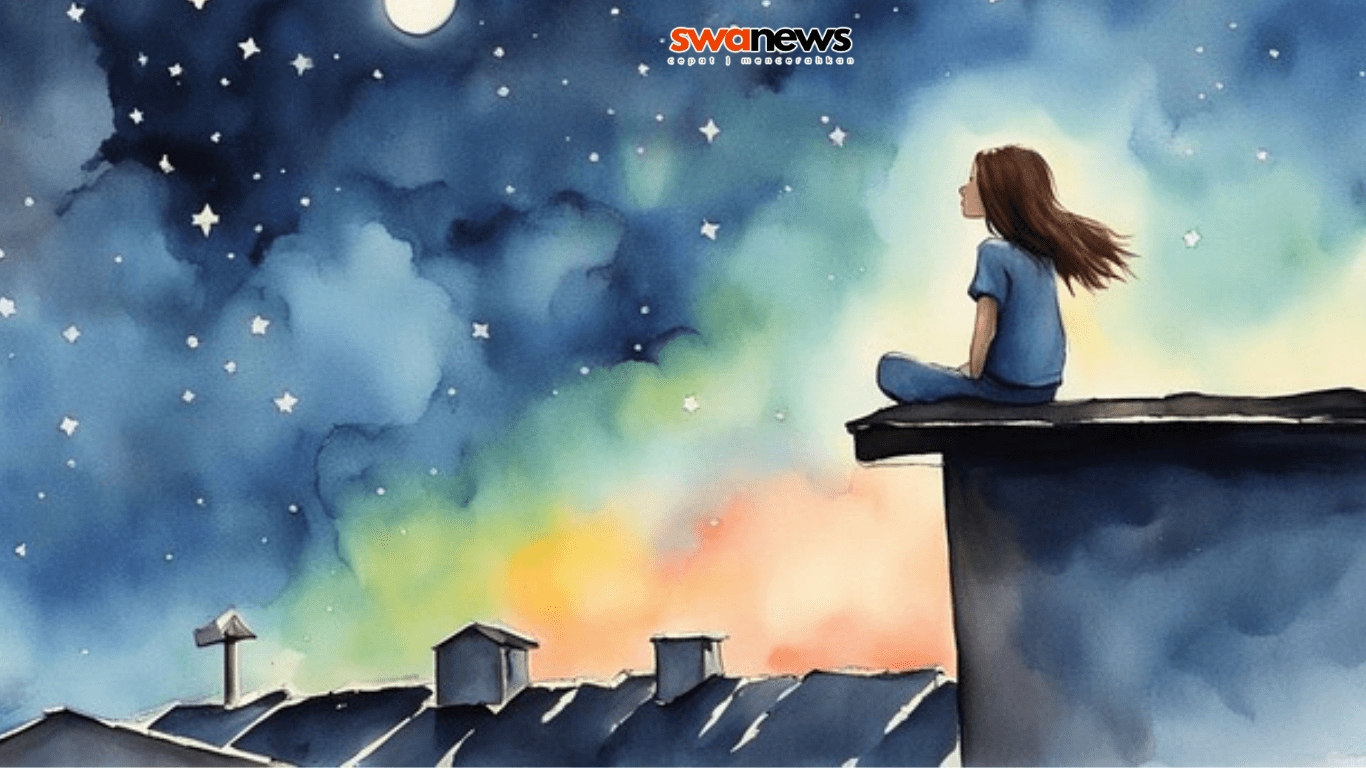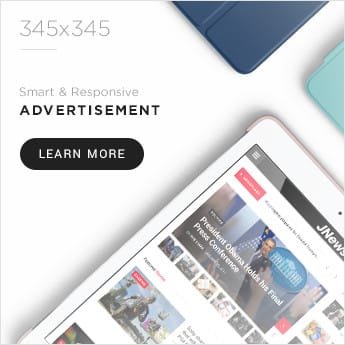Gadis Kecil, Milyarder, Totalitas Perubahan Nasib
Oleh Hamid Basyaib
PADA suatu malam Oktober yang sejuk, pusat kota Chicago berkilauan diterpa cahaya senja. Di Marlowe’s — restoran tepi sungai yang meraih bintang Michelin—Richard Evans makan sendirian.
Ia berwibawa dan pendiam, dan dikenal di lingkaran real estate karena ketegasannya dalam berbisnis dan ketenangannya yang sekeras baja.

Rambutnya yang mulai memutih tertata rapi. Rolex di pergelangan tangannya berkilau di bawah lampu meja. Steak ribeye yang telah matang sempurna menanti suapan pertamanya.
Bisik-bisik selalu mengiringi setiap langkah Richard Evans. Kekaguman berpadu dengan kewaspadaan terhadap dirinya. Ia membangun kerajaan bisnis, namun tak banyak orang yang sanggup melihat ke balik sosok setegar granit itu.
Tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan malam itu.“Pak, bolehkah saya makan bersama Bapak?”
Evans mengangkat kepala. Seorang gadis kecil—bertelanjang kaki, tak lebih dari sebelas tahun—berdiri di samping mejanya. Rambut kusut membingkai wajahnya yang kotor berdebu, dan matanya menyimpan kesepian yang tak butuh terjemahan. Manajer restoran hendak menghalau, tapi Evans mengangkat tangan menahannya.
“Siapa namamu?” tanyanya sambil melipat serbet dengan hati-hati.
“Emily,” jawabnya, sambil melirik ke arah para tamu lain. “Saya belum makan sejak hari Jumat.”
Evans menunjuk kursi kosong. Suasana restoran kontan hening ketika gadis itu naik ke kursi. Kakinya menggantung di udara. Saat pelayan datang, Evans hanya berkata, “Bawakan steak saya untuknya. Dan segelas susu hangat.”
Emily makan perlahan, nyaris penuh rasa khidmat. Ia seperti khawatir makanan langka itu bisa lenyap sewaktu-waktu.
Ketika piringnya bersih, Evans mendekatkan wajah. “Di mana keluargamu?”
Emily menjawab dengan terbata-bata: ayahnya meninggal karena terjatuh, ibunya sudah lama menghilang entah ke mana, dan neneknya baru saja meninggal. Hening membungkus meja itu.
Baca juga: Tuhan dalam Jebakan Post Truth
Richard Evans menggenggam gelas airnya. Ia dihantui bayangan masa lalunya sendiri.
Hampir tak ada yang tahu bahwa ia pernah hidup di trotoar dingin yang sama—mengumpulkan kaleng, tidur di samping radiator di gedung kosong. Ia tahu sejak dini bahwa suara lapar lebih nyaring daripada harga diri. Ia merangkak naik, berjanji pada diri sendiri: bila suatu hari ia berhasil keluar, ia akan meraih tangan orang lain.
Kemudian ia berdiri, mengeluarkan dompet—bukan untuk memberi uang, melainkan sesuatu yang lebih.
“Maukah kamu ikut pulang denganku?” tanyanya.
Emily berkedip. “Maksudnya?”
“Maksud saya, tempat untuk tidur. Makanan sungguhan. Kesempatan sekolah. Tapi harus dengan usaha dan rasa hormat. Tak ada lagi kelaparan.”
Emily mengangguk. Air mata menggantung seperti manik kaca di tepi keyakinannya.

Malam itu, segalanya berubah.
Emily bertemu kehangatan—air panas, seprai lembut, mukjizat sampo dan sikat gigi. Namun kebiasaan bertahan hidup tak mudah hilang.
Ia tidur meringkuk di lantai dan menyembunyikan roti gulung di dalam sweter. Saat pembantu rumah menemukan simpanan biskuitnya, Emily menangis. Evans berlutut di sampingnya, suaranya mantap: “Kamu tak perlu takut lagi.”
Dalam bimbingannya yang tenang, Emily berkembang. Ia belajar giat, digerakkan oleh keteguhan yang tak jauh beda dari Evans sendiri. Ia diberi tutor, didukung minatnya, dan keberhasilannya tak pernah dipamerkan.
Hampir tiap malam mereka berbincang sambil menghirup cokelat panas—pecahan kisah pedih Evans muncul dalam pengakuan lirih: malam-malam tanpa atap, tatapan orang-orang yang melihat namun seolah menembus dirinya.
Waktu berlalu, Emily akhirnya melangkah di panggung wisuda Columbia sebagai lulusan terbaik. Pidatonya bukan soal nilai GPA—melainkan tentang trotoar, steak, dan jawaban seorang pria pada permohonan gadis kecil asing yang kumuh.
“Kisah saya dimulai dengan lima kata: ‘Bolehkah aku makan bersama Bapak?’ Richard Evans mengubah hidup saya dengan satu tindakan kebaikan.”
Ia tak mengejar Wall Street. Sebaliknya, ia mendirikan Can I Eat With You?Foundation, yayasan yang mendedikasikan diri untuk memberi makan, tempat tinggal, dan pendidikan bagi anak-anak tunawisma. Richard Evans menyumbangkan sepertiga hartanya untuk mengawali misi itu.

Gadis kecil
Dan kini, setiap 15 Oktober, mereka kembali ke Marlowe’s—bukan untuk duduk di dalam, melainkan memenuhi meja di trotoar. Hidangan hangat. Pelukan terbuka. Tanpa pertanyaan.
Karena dulu, kasih sayang pernah duduk di meja itu. Dan ia tak pernah pergi.
Penulis dan Wartawan Senior